Saling meminta dan memaafkan setelah berpuasa selama 29 atau 30 hari, utamanya dilakukan setelah salat Ied adalah bagian dari tradisi. Tradisi lebaran itu, kata budayawan Umar Kayam, merupakan terobosan akulturasi budaya Jawa dan Islam yang tumbuh dan berinovasi.
Kabarnya Sunan Kalijaga memperkenalkan kupatan menyambut lebaran. KGPAA Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa, konon merintis sungkeman dan halal bihalal. Para ulama dan tokoh masyarakat mempopulerkan maaf-maafan demi menjaga kerukunan.
Inovasi yang dimaksud Umar Kayam mungkin merujuk pada perubahan yang sesuai dengan konteks zaman. Sayangnya saya menangkap inovasi ini seolah hanya dilakukan oleh para elite. Kaum alit sedikit sekali perannya.
Namun, tampaknya Umar Kayam juga menyadari bengkoknya inovasi sehingga melahirkan tiga Cerita Pendek (Cerpen) tentang orang-orang yang digilas tradisi. Tentang orang-orang miskin. Korban komodifikasi tradisi.
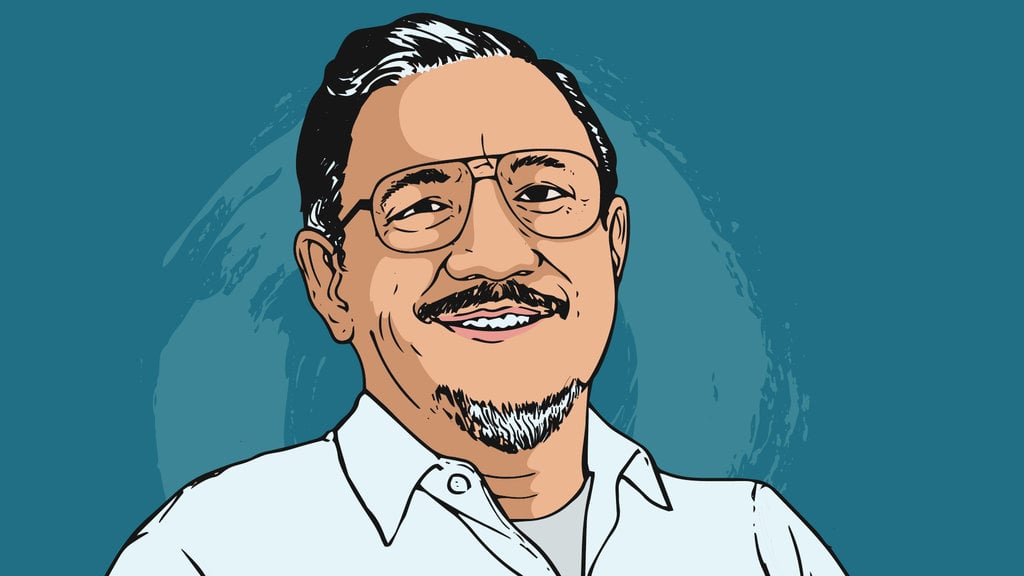
Cerpen pertama “Ke Solo, Ke Njanti”. Seorang ibu bersama dua anaknya gagal merayakan lebaran di kampung halaman karena tidak dapat masuk ke dalam bus akibat penuhnya penumpang. Padahal karcis sudah dibeli. Padahal, sang ibu sudah mempersiapkannya selama tiga tahun. Tokoh ibu bersama anaknya itu pun akhirnya kembali lagi bekerja pada majikan mereka sambil menahan kecewa.
Dalam “Menjelang Lebaran” keluarga Kamil juga gagal memenuhi janji pada anak-anaknya untuk lebaran di kampung karena kena PHK. Cerpen “Sardi” lebih muram. Tokoh Sardi dipengaruhi setan, menggelapkan uang majikannya agar bisa lebaran di kampung.
Gaji satu bulan Sardi hanya cukup membiayai perjalanannya. Mampus dia kalau tidak bawa apa-apa ke hadapan sanak saudaranya. Lagipula sudah tradisi, perantau memberi uang atau barang ke sanak saudara ketika pulang kampung, sehingga ia tak berpikir dua kali mencuri harta juragannya lalu dibagikan pada keluarga.
Tiga cerpen itu terbit 23 tahun lalu.
Bila latar yang ditulis Umar Khayam diperas dari proses mimesis, maka tidak ada yang benar-benar berubah dari masyarakat selama 23 tahun ini. Barangkali, di sekitar ada jutaan para ibu, Sardi, dan Kamil yang gagal lebaran karena dampak carut marutnya ekonomi, politik, dan hukum.
Kaum elite memanfaatkan lebaran untuk berpolitik. Meminta maaf setelah menggergaji gunung, mencukur hutan, mencepak sawah, menyerobot tanah, memukuli sekaligus menembaki demonstran, mengasapi suporter, dan membuat produk hukum di luar nalar.
Suharto, dalam pidato idul fitri tahun 1973 dan 1974, bahkan pernah menyampaikan ancaman dengan kalimat paling lembut. Pertama, mengajak rakyat bekerja keras dalam kehidupan bernegara dan agar menjauh dari prasangka buruk yang memperlambat pembangunan. Kedua, dengan kata yang sama, ‘mengajak’ rakyat tidak mengkritik ketidakberhasilan pembangunan.
Agaknya, dalam waktu dekat—mungkin saja sudah terjadi—kita akan diberondong wacana-wacana serupa. Diminta maklum. Mungkin, di tengah chaos dan kekerasan. Di tengah kesewenang-wenangan dan keangkuhan kekuasaan yang sedang kita saksikan, ada ketakutan panjang sehingga kita cenderung melarikan diri dari kompleksitas persoalan lalu acuh dengan sekitar. Dan tanpa disadari kita memberi maaf pada kejahatan, atas nama tradisi.










Leave a Reply